
Siapa di Hari begini yang belum pernah merasakan kisah di tanah rantau? Sepertinya, walaupun mungkin hanya dalam waktu singkat, banyak yang sudah pernah merasakan merantau.
Tetapi, dari yang sudah sering melakukan aktivitas merantau, mungkin hanya sebagian kecil saja yang menyadari, bahwa banyak sisi baik dalam karakter Kita tumbuh dan berkembang saat merantau.
Ngga, percaya?
Yuk, simak kisah di bawah ini. Niscaya kamu akan mengakui kebenarannya.
Kursus Bahasa Tercepat
“Sikilku kesel,” Inung berkata sambil selonjor di sampingku.
Aku yang mendengar kata-katanya, mengerutkan kening. Kaki kok bisa kesal? Aneh. Aku bingung. Tapi tak ada yang akan menjelaskan apa pun padaku dalam Bahasa Indonesia. Karena semua teman sudah sepakat, untuk membiarkan aku belajar bahasa ini dengan mendengar dan langsung praktek, bukan penjelasan.
Baiklah! Aku tunda bertanya untuk penjelasan kali ini. Karena, sekarang aku sedang kerepotan memahami cerita teman-teman yang sedang leyeh-leyeh di teras kamar kost-kost an kami. Suara mereka tumpang tindih tidak karuan. Sehingga seperti dengungan suara tanpa makna di telingaku.
Meskipun aslinya cerewet, akhirnya aku terpaksa hanya memasang mimik datar dan diam mendengarkan semua percakapan. Itu langkah paling aman. Dari pada aku pura-pura mengerti dan harus menjawab pertanyaan dalam Bahasa Jawa. Alamat jadi bahan tertawaan…
Begitu terus yang terjadi setiap hari.
Meski aku belajar dengan cepat. Tapi tidak secepat yang aku harapkan untuk bisa memahami bahasa yang memiliki 3 tingkatan kesopanan ini. Jadinya, saat praktek lapangan di masyarakat pun, aku masih terpatah-patah mengucapkannya. Masih terbengong-bengong juga memahami kalimat yang tidak logis di telingaku. Bayangkan saja,
“ditanduri nopo bu?” itu salah satu pertanyaan dalam list kuesioner kami
“ditanduri pantun,” ibu tadi menjawab ramah
Aku beneran bingung mendengarnya. Pantun memangnya tanaman, ya? Tapi setelahnya, ketika kami beristirahat dari proses wawancara lapangan, penjelasan teman-teman membuatku terbahak-bahak menertawakan kebodohanku sendiri. Meskipun aku juga tidak terima disalahkan. Karena pantun kan memang ada di Bahasa Indonesia. Mana aku tahu, kalau itu sebutan halus untuk padi.
Sampai beberapa bulan pertama, aku juga masih selalu tertukar tiap kali mengucapkan matur suwun dengan nuwun sewu. Sehingga selalu menjadi tertawaan teman-teman ketika keliru mengucapkannya. Maksudnya, aku mengucapkan nuwun sewu saat berterima kasih, atau sebaliknya.
Memang, buat banyak orang, kejadian-kejadian seperti itu seringkali membuat malu. Namun, aku tak pernah memasukkan semuanya ke dalam hati. Mungkin, ini salah satu keuntungan dibesarkan dengan tradisi Betawi yang cuek. Jadinya, aku tidak mudah baper menerima apa pun, termasuk dijadikan lelucon.
Aku sih, masih mending. Teman-teman yang mendampingiku, semuanya fair. Mereka berbicara dalam bahasa umum yang benar, bukan yang menyesatkan. Temanku Irfan yang berasal dari Bima – Nusa Tenggara Barat, tidak seberuntung aku. Teman-teman kost nya kadang menjejali dia dengan kata-kata tidak sopan.
Suatu kali, ketika Irfan menanyakan kata-kata untuk menyapa orang tua saat berpapasan, mereka menyuruhnya mengucapkan segawon. Irfan yang dengan polosnya mengucapkan kata itu ke tetangganya, tentu saja kena marah. Teman-temannya hanya berlari sambil terbahak-bahak melihat Irfan yang ketiban marah.
Tidak hanya teman-teman yang membuat bahasa menjadi kendala dalam interaksiku. Karena ternyata, para dosen pun terkadang menggunakan bahasa daerah dalam memberikan penjelasan mata kuliah. Bila itu terjadi, aku hanya bisa mendengarkan sambil mengira-ngira maksudnya. Baru setelah kuliah berakhir, aku menanyakan artinya kepada para sahabatku.
Meningkatnya Daya Adaptasi
Sebenarnya, tidak hanya bahasa yang membuat hidupku di kota ini menjadi penuh warna. Tradisi, budaya dan adat istiadat yang begitu jauh berbeda dengan kehidupan di Ibukota, juga memberi warna tersendiri dalam interaksiku. Teman-temanku yang sebagian besar memang dibesarkan di tanah Jawa ini, punya karakter yang hampir sama. Lemah lembut dalam berbicara, sederhana dan cenderung perlahan dalam mengerjakan sesuatu.
Berbeda dengan kebiasaan di kota kelahiranku. Di sana, dengan iramanya yang cepat, membuat penghuninya terbiasa melakukan segala sesuatu dengan bergegas.
Lihat saja efeknya sekarang
Meski sudah berusaha berjalan sepelan yang aku bisa, tetap saja posisi berjalanku selalu paling depan. Itu selalu terjadi tiap waktu kami berjalan bergerombol saat kuliah atau ketika jadwal kelas di kampus pusat. Akhirnya, karena kesal selalu menunggu lama di depan, aku mulai berhenti berjalan tiap beberapa langkah. Hanya agar tidak terlalu jauh meninggalkan teman-teman di belakang.
Begitu juga dengan cara bicaraku yang lantang dan cepat. Begitu kontras dengan suara mereka yang kebanyakan lembut dan mendayu. Aku tidak bilang, itu kelemahan. Tapi, semua benar-benar berbeda. Namun, sepertinya semua bukan masalah besar buatku.
Meskipun masih terus terbata-bata merbicara menggunakan Bahasa Jawa. Juga menyesuaikan kecepatan langkah dan caraku berbicara. Selain itu, tak ada kendala lain yang berarti, kecuali ketika teman-teman pulang ke rumah masing-masing di awal bulan..
Keliling Pulau dengan Biaya Minim
Perjalanan dari ibukota ke daerah tempat kampusku berada, menghabiskan waktu kurang lebih 12 jam lamanya dengan kereta api atau bis AKAP. Perjalanan yang cukup melelahkan. Sehingga rasanya aku hanya bisa pulang saat liburan semester, ketika kuliah libur selama lebih dari 2 minggu.
Tadinya aku pikir, begitu juga yang dilakukan teman-teman yang lain. Mereka pulang, hanya saat liburan panjang. Tapi, ternyata perkiraanku salah. Hampir semuanya pulang setiap dua minggu atau sebulan sekali. Bahkan, mereka yang rumahnya sama-sama di Semarang – hanya berbeda kecamatan, pulang pergi setiap hari.
Saat pertama kali para sahabat pulang ke tanah kelahiran masing-masing di awal bulan, mendadak lingkungan kost lengang. Sepi dari aktivitas. Apalagi di kost-an ku. Dari 20 kamar yang ada di sana, hanya kamarku yang berpenghuni. Ditambah ibu kost dan keluarganya. Saat itu lah, baru terasa sepinya hidup jauh dari keluarga.
Malam pertama tanpa teman, ternyata benar-benar membuatku menangis kesepian. Aku yang selama ini selalu ceria penuh tawa. Ternyata bisa juga merasakan kesepian seperti ini. Tak ada teman satu pun yang bisa diajak bercerita dan mengobrol seperti biasa. Tidak ada juga rekan yang bisa berbagi makanan. Rumah kost benar-benar lengang.
Untuk ikut-ikutan pulang ke ibukota, tidak mungkin. Dengan uang saku bulanan yang hanya cukup buat kost dan biaya makan. Tidak mungkin aku sisihkan untuk biaya tiket kereta pulang pergi. Menghabiskan jatah, menyusahkan ibu juga nantinya. Jadi, mau tidak mau, aku harus melalui 2 hari ini sendiri. Benar-benar sendirian.
Menangis sendiri dalam kesepian seperti itu, masih terus aku lalui selama beberapa bulan berikutnya. Tanpa punya pilihan lain.
Pembelajaran Pengelolaan Keuangan Terbaik
Seharusnya, soal keuangan biasa menjadi masalah utama di antara banyak masalah yang dihadapi anak rantau. Tingginya biaya hidup dan kecilnya uang kiriman, selalu membuat banyak mahasiswa mencari hutangan di rumah makan atau ibu kost. Tapi, syukurlah, itu tidak menjadi masalah buatku.
Bukan berarti kirimanku teramat besar. Bukan… Meskipun aku berasal dari ibukota, orang tuaku hanya warga kebanyakan dengan penghasilan secukupnya saja. Jadi, dari kiriman orangtuaku setiap bulan, setelah dipotong separuhnya untuk kost, sisanya cukup untuk makan satu bulan. Hitungannya begitu.
Setelah berembug dengan 3 kawan sefakultas yang juga kost di sini, kami memutuskan untuk bersama-sama menanggung biaya makan satu bulan. Untuk bumbu, mereka cukup membawa dari rumah. Setelah berjalan beberapa bulan, ternyata cara ini benar-benar menghemat uang saku kami. Karena, hanya dengan patungan sebesar sepersepuluh uang sakuku, kami berempat bisa memenuhi kebutuhan makan selama sebulan. Sungguh sangat menguntungkan.
Cara itu juga membuatku, mampu menyisakan uang yang lumayan besar – menurut ukuranku. Akhirnya aku berpikir menggunakannya untuk nunut para sahabatku, saat mereka pulang awal bulan. Agar aku tak kesepian lagi di kost-kost-an.
Memang, sejak saat itu, aku memang selalu ikut teman-teman saat mereka pulang. Bergantian. Dengan begitu, masalah kesepianku saat awal bulan jelas berakhir. Selain itu aku juga bisa keliling Jawa – jalan-jalan dengan menumpang di rumah para sahabatku.
Membangun Jejaring
Memiliki teman dari berbagai daerah, meskipun dengan budaya yang hampir sama, ternyata tidak berarti sama juga perilakunya. Teman seangkatanku ada 40 orang lebih. Berarti, sejumlah itu pula jenis sifat berbeda yang harus aku hadapi. Kebanyakan tidak membuat masalah. Hanya 1 atau 2 orang saja, yang pernah berselisih paham denganku. Itu pun tidak terlalu lama. Aku memilih mengalah, ketimbang harus bertengkar, apa pun sebabnya.
Sepertinya, dengan merantau begini, jauh dari orang tua dan keluarga, membuat daya adaptasi dan tingkat mudah mengertiku melesat tinggi. Apalagi, karena masih kesulitan memahami bahasa setempat, aku lebih sering menjadi pengamat dan memperhatikan semua teman dan sahabat.
Meskipun ada saat-saat kelabu, kebanyakan hariku diisi dengan persahabatan dan keceriaan. Walaupun ada 1 atau 2 perselisihan, tapi tidak pernah membuat persahabatan kami terganggu. Apalagi menjadi rusak.
Seperti itu juga interaksiku dengan teman satu kost. Dengan tambah beragamnya penghuni kost – yang menuntut ilmu dengan disiplin berbeda dariku. Memang tidak jarang menyulut kesalahpahaman. Tetapi dengan saling mengerti dan memahami, kesenjangan seperti itu dengan mudah terlewati
Nah, gimana? Setuju kan kalau merantau merupakan kawah Candradimuka juga buat sebagian besar dari Kita, yang di dalamnya banyak kebaikan untuk mengembangkan karakter baik. Walaupun, mungkin juga sedikit sifat jelek yang.
Jadi, sudah tidak ragu lagi membiarkan putra dan putri Kita merantau untuk menuntut ilmu?
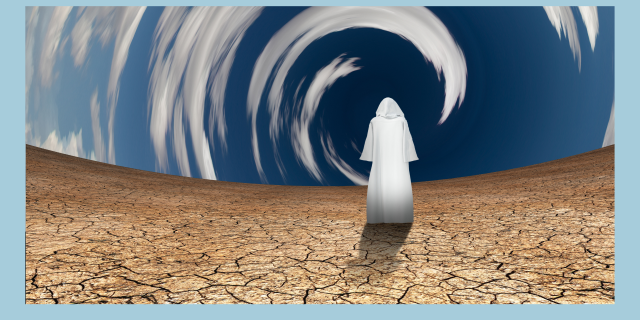





No Responses